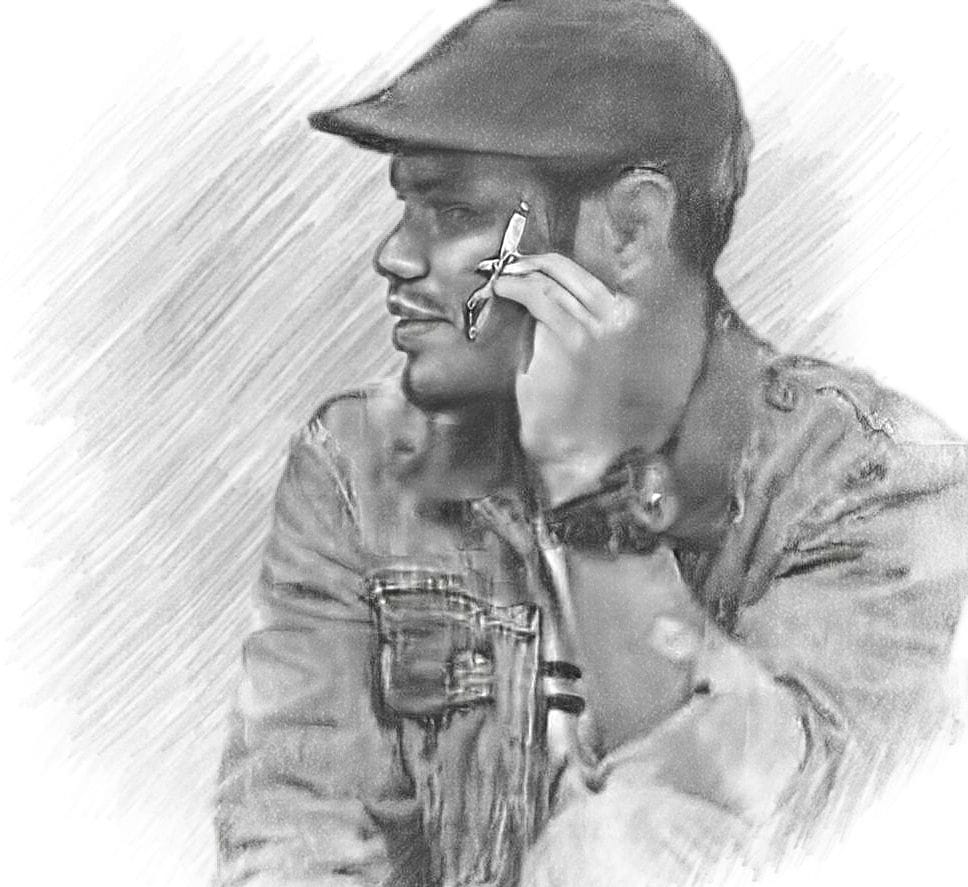
Oleh: Hancel Goru Dolu*
Pemilu adalah etalase. Pada etalase, setiap pengunjung disodorkan aneka pilihan. Ragam pilihan itu, pada akhirnya, diharapkan untuk dibeli. Dalam dunia politik Indonesia, pemilik etalase tersebut adalah partai-partai politik. Isi etalase, tentu saja, adalah para kandidat yang disodorkan. Rakyat pemilih yang menjadi pengunjung, bisa ‘membeli’ isi etalase tersebut, di tempat pemungutan suara.
Maka, jadilah lima tahun sekali, orang-orang ‘baik’ seringkali muncul secara masif. Momen penyelenggaraan pemilihan umum jadi penyebab utama terjadinya fenomena ini. Orang-orang yang diandaikan baik itu mewujud dalam diri mereka-mereka yang terlibat dalam pertarungan sebagai calon anggota legislatif atau peserta kontestasi elektoral lainnya. Petarungan orang-orang dalam etalase!
Oleh karena isi etalase adalah kumpulan manusia, maka bolehlah kita membayangkan rumah kaca salon kecantikan ataupun mega akuarium. Dengan motif agar dilirik, hadirnya aneka riasan adalah keniscayaan. Orang-orang yang ‘nyalon’ (baca: calon) itu pun ‘nyalon’ (baca: merias) di etalase salon.
Kepentingan bangsa, kebaikan bersama, persatuan, kesejahteraan, kebhinekaan, toleransi, dan hal-hal baik lainnya; adalah hasil dari riasan salon tersebut. Sales dengan aneka teknik marketing dalam diri para buzzer tanpa henti membuat promosi. Lalu para rakyat pengunjung yang menjadi langganan lima tahun sekali itu, riuh memilah dan memilih, pun terbelah dan berselisih.
Mungkin ada yang tak sepakat dengan analogi etalase salon. Tapi, barangkali memang begitulah faktanya. Para sales politik tak jarang mendengungkan jargon “jangan membeli kucing dalam karung.” Mungkin itu dimaksudkan sebagai imbauan pada para rakyat pengunjung agar benar-benar secara mendalam memahami produk yang mereka pilih. Sepintas, itu terdengar baik adanya.
Namun, pertanyaannya kemudian adalah: mengapa dianalogikan dengan kucing, hewan manipulatif yang oleh sebuah lagu dangdut disebut suka menggarong? Mengapa kucing-kucing itu layak dan harus dibeli? Mengapa kucing yang tak layak dibeli ikut dijajakan? Mengapa harus takut pada kucing di dalam karung, jika kucing yang tak berada di luar karung itu benaran manis dan menyenangkan? Pendeknya, mengapa masih harus dibingkai dengan riasan kosmetika pencitraan kampanye, kalau memang punya rekam jejak ide dan tindakan yang melekat di sanubari rakyat pemilih?
Jargon tersebut adalah pengakuan tak langsung, bahwasanya secara faktual, politik adalah transaksi. Kompetisi politik hanyalah perihal jual-beli. Dalam praktiknya, bisa dengan gamblang dilihat pada berbagai pemberitaan, seringkali dijumpai aneka tukar tambah kepentingan. Istilah-istilah seperti mahar, serangan fajar, money politics, hingga gratifikasi, beredar luas.

Salon Politik
Di masa lampau, salon pernah jadi tempat berkumpul para pemikir, sastrawan, dan orang-orang politik. Revolusi Prancis, salah satunya lahir dari percakapan dan konsolidasi di ruang salon. Pemilik salon biasanya berasal dari kalangan borjuis. Borjuis ini adalah kelompok yang kelak mengklaim hasil revolusi para kaum pekerja dan masyarakat marjinal lainnya.
Di ruang salon, apa saja bisa dirias. Pada pengalaman revolusi Prancis, bahkan ada konsolidasi di sana. Dalam ‘marketing’ politik, hal yang demikian merupakan bagian dari strategi-taktik. Lakunya isi etalase adalah indikator kemenangan dalam kontestasi Pemilu. Dan kemenangan, selalu berkait erat dengan pragmatisme yang seringkali pula membuka pintu bagi manipulasi, aneka tendensi, dan jebakan riasan kosmetik lainnya. Suasana pemilu hampir selalu melahirkan para politisi salon.
Dr. Muhammad Amir memperkenalkan istilah ‘Salon Politicus’, dalam sebuah buku bertajuk Bunga Rampai, kumpulan karangan yang terbit pada tahun 1923-1939. Salah satu pendiri Jong Sumatra itu menyoroti golongan pejuang yang hanya manis berkata-kata. Membangun citra sebagai pejuang keadilan, tapi, menurutnya, tak semua kaum pergerakan itu mau memikul konsekuensi dari keyakinannya. Ujung-ujungnya, kata Amir, kaum oportunis ini memasuki kancah politik untuk mengisi saku sendiri.
Kritik Amir di atas, tampaknya relevan dengan situasi hari-hari ini, di sini-kini. Tanpa kaderisasi yang jelas dan terukur, tiba-tiba bermunculan aneka calon. Beberapa memang punya kapasitas yang jelas rekam jejaknya. Tapi tak sedikit yang mengandalkan ‘isi tas’, dinasti politik, kolusi, popularitas keartisan, kader ‘kutu loncat’, dan aneka motif pragmatisme lainnya.
Selain kontestasi para calon, partai-partai politik juga sedang bertarung dengan menurunnya kepercayaan warga pada partai dan dunia politik. Berbagai survei dan hasil pemilihan umum menampilkan fakta tersebut. Kemenangan kotak kosong beberapa waktu silam pun telah menjadi kisah bersejarah. Belum lagi kini partai-partai politik dihadapkan dengan regulasi ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen itu sendiri adalah batas suara minimal partai politik dalam Pemilu untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi DPR. Politik salon diperkirakan bakal makin dan terus masif terjadi. Para sales politik dihadapkan pada situasi imperatif sine quo non, mau tidak mau, harus ekstra keras mencapai target minimal tersebut.
Demikianlah situasi salon tempat para calon masuk ‘nyalon’ demi dilirik para pelanggan setia lima tahunan. Banyaknya jumlah pesaing, menurunnya kepercayaan warga pada partai politik, dan naiknya syarat ambang batas parlemen; adalah beberapa hal yang melatari aquarium salon bagi yang ‘nyalon’. Aneka gaya politik yang lebih canggih pasti akan silih berganti dipamerkan jelang hari-hari menuju tempat pemungutan suara.
Politik salon, menurut Israr Iskandar dalam tulisannya yang berjudul “Politisi Salon”, adalah usaha meraih kekuasaan mengandalkan pencitraan politik untuk mempengaruhi atau tepatnya membentuk opini tertentu sesuai keinginan sang politisi atau partai.
Politisi salon, jelas Israr, tentu saja menganut paham pragmatisme oportunistik. Dengan mengandalkan modal, sistem yang korup, dan masyarakat yang sedang mandek, mereka melakukan berbagai cara membentuk pencitraan politik sesuai yang dikehendaki. Mereka akhirnya tak hanya melanggar batas etika politik, tapi juga melecehkan akal sehat publik.
Di setiap perhelatan pemilu, tampaknya akal sehat publik terus dilecehkan. Sebab dunia politik selalu menjadi mega akuarium salon. Di situ para politisi silih berganti merias diri dan membangun citra. Sebagai akibatnya, sebagian besar rakyat terbelah ke dalam politik idola dan patronase. Kebijakan-kebijakan publik kemudian tak secara mengakar-mendasar disikapi. Argumen hilang, berganti sentimen. Politik kemudian dimaknai sekadar merebut kekuasaan belaka. Manusia Politik yang lebih maju jadi semacam utopia.
Manusia Politik
Manusia Politik berbeda dengan Politisi. Demikian kata Budiman Sudjatmiko. Politisi, kata eks aktivis PRD yang melawan rezim Orde Baru itu, adalah orang-orang yang hanya punya hasrat untuk memperoleh kekuasaan. Seperti dijelaskan di atas, untuk memperoleh kekuasaan, politisi cenderung memainkan gaya politik salon. Aneka slogan dan hipokrisi senantiasa jadi identitas diri.
Budiman menyodorkan opsi Manusia Politik, “I am not politician, I am a political man”. Manusia politik itu sendiri, terang Inisiator UU Desa itu, memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat yang sekiranya membantu para pemilih untuk memilah dan memilih, agar tak terjebak pada pilihan politik salon. Kriteria lengkap yang harus dimiliki oleh mereka-mereka yang ingin mengurus kepentingan publik.
Pertama, harus memiliki ide-ide dan bergelut dengan berbagai gagasan yang progresif. Gagasan adalah bandul yang menuntun langkah-langkah politik setiap Manusia Politik. Visi besar yang ditawarkan, harus bisa dipertarungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan gagasan-gagasan lain. Seorang manusia politik, tak pelak, adalah individu yang gandrung pada dialektika. Sehingga konservatisme ataupun feodalisme tak punya tempat dalam iklim politik yang akan dibangun kelak.
Tentang otentisitas pemikiran, Mohamad Sobary telah mewanti-wanti dalam tulisannya yang berjudul “Pemimpin Kelas Salon”. “Haruskah kita memercayai kesimpulan yang tampak logis bahwa kini perkembangan kesadaran politik bangsa kita baru sampai tahap mengagumi foto, kata-kata, dan tampilan ‘rapi jali’ buatan salon yang memiliki selera kecantikan, tetapi sama sekali -dan dengan sendirinya- tak memiliki otentisitas pemikiran tentang pemimpin dan kepemimpinan?”
Kedua, punya pengalaman berorganisasi. Organisasi itu sendiri merupakan tempat ide-ide ataupun gagasan dipraksiskan. Ide-ide hanya akan menjadi utopia, jika sekadar memenuhi isi kepala belaka. Sejarah pergerakan nasional Indonesia adalah contoh terbaik tentang ini. Anak-anak muda dengan aneka gagasan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dengan aneka organisasi modern (partai politik).
Ketiga, memiliki empati pada nasib orang banyak. Poin ini yang, mungkin, paling banyak diucapkan para politisi hari-hari ini. Ini pula yang membuat saya, di awal coretan ini, menyebutkan bahwa lima tahun sekali orang-orang baik selalu muncul secara masif. Sebab, apa guna negara dan para politisi jika nasib orang banyak tak diperhatikan secara baik dan benar? Jika ide-ide atau gagasan bisa dipertarungkan, maka poin empati ini bisa dicek pada rekam jejak setiap mereka yang berkontestasi.
Keempat, memiliki hasrat berkuasa. Poin ini yang mungkin paling malu-malu diucapkan oleh para politisi. Tapi, kita semua tampaknya sepakat, bahwa inilah poin utama yang melandasi semua hingar-bingar dunia politik. Semua politisi punya hasrat berkuasa! Dengan berbagai latar belakang, motif, dan tujuan-tujuan tertentu. Menjadi manusia politik artinya memakai kekuasaan untuk mewujudkan gagasan-gasan progresif demi kebaikan bersama orang banyak. Bukan untuk kelanggengan korporatokrasi atau kepentingan segelintir kelompok atau orang.
Kelima, sebagai bonus, punya kemampuan retorika yang baik. Manusia politik dengan segala kecakapan yang dimilikinya, mustilah individu yang mampu bersosialisasi dan menyampaikan gagasan-gagasannya secara baik. Rocky Gerung, dalam tulisannya yang berjudul “Demagogi” (Tempo, 07/07/2014), mengingatkan publik untuk jeli pada kalimat politisi: pedagogi atau demagogi. “Debat adalah seni persuasi. Seharusnya ia dinikmati sebagai sebuah pedagogi: sambil berkalimat, pikiran dikonsolidasikan. Suhu percakapan adalah suhu pikiran. Tapi bagian ini yang justru hilang dari forum debat hari-hari ini. Yang menonjol cuma bagian demagoginya: busa kalimat. Pada kalimat berbusa, kita tak menonton keindahan pikiran,” tulis Rocky.
Hari-hari ini, publik bisa menilai apakah Politisi Salon yang berdemagog ataukah pedagogi Manusia Politik yang telah dan akan mereka pilah juga pilih. Atau mungkin juga, Manusia Politik dengan kriteria lengkap seperti di atas, memang tak ada. Bahkan termasuk pada Budiman itu sendiri, mungkin. Akhirnya, selamat nyalon di salon, selamat melihat-lihat isi etalase yang telah dan akan dipamerkan!
*) Ditulis pada Agustus 2018. Penulis adalah orang Ngada, founder & pengelola HorizonDipantara.com, dan suka menonton pertandingan dari belakang gawang.
Leave a Reply